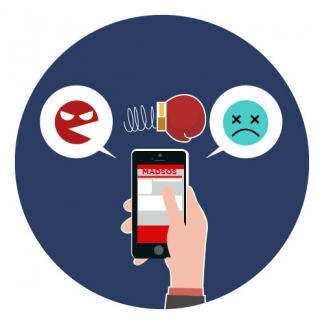Ironisnya, aparat penegak hukum menjerat pasal yang seharusnya untuk bandar, pengedar, atau kurir kepada penyalahguna atau pecandu narkotika.
Eric Manurung. Foto: Istimewa
Jenis Golongan Narkotika
Isu narkotika sudah lama menjadi permasalahan negeri ini. Perkembangannya sangat signifikan, merebak dari kota sampai ke desa, penggunanya mulai dari artis, pilot, pejabat, rakyat biasa, hingga oknum penegak hukum pun banyak yang menikmatinya. Aturan yang ada selama ini dianggap belum cukup efektif menangani permasalahan ini.
Sebagai wujud dari keseriusan negara untuk menangani permasalahan narkotika yang semakin merebak sampai ke pelosok negeri, maka aturan yang telah ada sebelumnya yakni UU No. 7 tahun 1997 diperbaharui dengan dibuat dan disahkannya UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Pengesahan UU ini, dilandasi karena tindak pidana narkotika dianggap sekarang telah bersifat trans-nasional, yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung jaringan yang kuat dengan jumlah nilai uang yang fantastis, dan banyak menjerat kalangan muda, generasi millenial.
Untuk memberi pemahaman yang jelas dalam UU ini, perlu mengikuti perkembangan mulai dari jenis narkotikanya, proses kejahatannya, hingga penyebutan istilah-istilahnya. Klasifikasi pembagian golongan narkotika pada UU ini, dibagi menjadi 3 jenis golongan yang termasuk kategori narkotika. Kategori pembagian jenis Golongan Narkotika adalah sebagai berikut:
- Golongan I , Jenis Narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Ganja, Sabu-sabu, Kokain,Opium, Heroin, dll;
- Golongan II, Jenis Narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Morfin, Pertidin dll;
- Golongan III, Jenis Narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Kodein, dll.
Seyogianya narkotika dapat digunakan dengan cara-cara yang diatur dalam UU. Narkotika juga dapat digunakan untuk penelitian, pendidikan, medis (kesehatan), dan lain lain. Namun dalam UU ini, juga diatur mengenai narkotika yang dimiliki, diproduksi, dibawa, digunakan tidak sesuai aturan atau secara melawan hukum.
Salah satu hal yang cukup mendetail dijelaskan juga dalam UU ini adalah terdapat klasifikasi pembagian “cap” bagi orang yang terlibat dalam narkotika. Pembagian klasifikasi pada UU ini berbeda pada pembagian secara umum yang sering disebut masyarakat yaitu pengedar narkotika dan pengguna narkotika. Namun dalam UU ini secara implisit dijelaskan lagi mengenai siapa saja yang dapat disebut pengedar berdasarkan perannya dan siapa saja yang dapat disebut Pengguna. Penjelasannya sebagai berikut:
- Pengedar Narkotika, terdapat beberapa penyebutan sesuai dengan perannya masing-masing, yakni:
- Pihak yang memproduksi Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 3 jo Pasal 113);
- Pihak yang Meng Impor Narkotika secara Melawan Hukum (Pasal 1 angka 4 jo Pasal 113);
- Pihak yang meng Ekspor Narkotika scara melawan hukum (Pasal 1 angka 5 jo Pasal 113);
- Pihak yang melakukan Pengangkutan atau Transito Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 9, 12 jo Pasal 115);
- Pihak yang melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskusor Narkotika (Pasal 1 angka 6 jo 111,112, 129).
- Pengguna Narkotika, juga terdapat beberapa penyebutan, yakni:
- Pecandu Narkotika (Pasal 1 angka 13 jo Pasal 54 jo Pasal 127);
- Penyalahguna Narkotika (Pasal 1 angka 15 jo Pasal 54 jo Pasal 127).
Sebenarnya sudah cukup jelas bagi masyarakat mengenai jenis-jenis narkotika yang dilarang diproduksi, dijual atau digunakan tanpa izin dari pihak yang berwenang yang diatur dalam UU ini. Jika masyarakat melanggar aturan dengan memproduksi, mengedar, memakai narkotika secara melawan hukum/tanpa izin (hak), maka sanksi pidanalah yang akan dijalani bagi masyarakat tersebut sesuai dengan peran perbuatan yang dilakukannya.
Penerapan Pasal-Pasal Pidana
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, mengenai golongan/jenis dan klasifikasi peran pihak yang berkaitan dengan narkotika, maka dalam UU ini telah diatur pula mengenai sanksi-sanksi pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan di atas. Bagi pihak yang memproduksi, pengedar/penjual atau perantara tentu sanksi hukumannya lebih berat dari pada pihak yang hanya menggunakan saja. Namun dalam klasifikasi pengedar pun dibagi lagi sesuai perannya, apakah sebagai pihak bandar besar yang memproduksi narkotika, atau hanya sebagai penjual saja, ataupun sebagai kurir/perantara saja.
Sanksi pidana dalam UU ini diatur mulai dari Pasal 111 s/d Pasal 148. Kurang lebih 37 Pasal mengatur mengenai sanksi-sanksi pidana yang dapat diterapkan atas perbuatan atau keadaan/peristiwa yang bermacam jenis. Namun dalam praktik yang terjadi, pasal yang mendominasi, secara umum sering digunakan para penegak hukum (BNN, polisi, jaksa, hakim) adalah Pasal 111, 112, 113, 114 Jo 132. Dan pasal yang jarang dikenakan adalah Pasal 127.
Adapun Pasal 111, 112, 113, 114 jo 132 adalah pasal sanksi pidana yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika untuk mengedarkan, menjual atau pihak yang menjadi kurir (perantara). Sedangkan Pasal 127 adalah pasal yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika sebagai penyalahguna atau pecandu.
Adapun sanksi penjara pada Pasal 111, 112, 113, 114 adalah minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Sedangkan sanksi pada Pasal 127 adalah rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun. Terdapat hukuman penjara yang cukup berbeda/signifikan antara pasal tersebut.
Dari penjelasan di atas, pada Pasal 1 angka 13 dan angka 15 UU ini mengatur mengenai dua klasifikasi dari pengguna narkotika (penyalahguna dan pecandu). Yang sesungguhnya menjadi semangat atau landasan filosofis dari diperbaharuinya UU Narkotika ini, selain untuk pencegahan dan pemberantasan narkotika, juga memiliki semangat untuk melindungi dan menyelamatkan para generasi muda yang telah menjadi pengguna narkotika.
Dalam UU ini, para pengguna narkotika disebut juga sebagai korban dari peredaran Narkotika tersebut. Karena semakin banyaknya peredaran narkotika, maka semakin banyak pula penyalahguna atau pecandu yang terjerat. Oleh karenanya negara/pemerintah dalam hal ini ikut campur dalam proses pencegahan maupun pemberantasan, namun juga pada proses penyelamatan/perlindungan bagi generasi muda secara masif yang telah banyak menjadi korban narkotika.
Negara/pemerintah membuat suatu badan yang khusus, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan tugas pokoknya menangani permasalahan Narkotika, bukan hanya pencegahan dan pemberantasan, namun juga sampai kepada tahap penyelamatan/rehabilitasi bagi orang yang telah terkena menjadi penyalahguna atau pecandu narkotika. Pemerintah juga memberikan anggaran yang cukup besar untuk membuat panti-panti rehabilitasi, dan bekerjasama dengan rumah sakit negeri maupun swasta untuk ikut menyelamatkan korban penyalahguna atau pecandu narkotika ini.
Yang menjadi persoalan atas penerapan pasal-pasal yang keliru dan sering digunakan aparat penegak hukum terhadap para penyalahguna narkotika adalah, adanya kerancuan/ambiguitas dalam pasal yang seharusnya dikenakan/diterapkan bagi bandar besar, pengedar, penjual atau kurir, namun dapat dikenakan juga pada korban penyalahguna atau pecandu narkotika. Hal ini dikarenakan pada Pasal tersebut terdapat unsur kata/frasa “memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika”.
Unsur frasa “memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika” inilah yang seharusnya dikenakan kepada pihak yang menjadi bandar, pengedar, atau kurir. Namun sering dikenakan kepada pihak penyalahguna atau pecandu narkotika. Sehingga Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan (LP) di seluruh penjuru negeri hampir 70% diisi oleh pelaku perkara narkotika. Tidak sedikit di antaranya adalah para penyalahguna atau pecandu narkotika, yang seharusnya bukan di situ tempatnya berada berdasarkan UU ini.
Hal ini, pernah dialami sendiri oleh Penulis dalam melakukan pendampingan dan pembelaan terhadap penyalahguna narkotika. Dua orang nelayan di Batam, yang berpendidikan dan berpenghasilan rendah, dengan bujuk rayu dari seseorang untuk coba menggunakan sabu-sabu, dengan efek akan semakin kuat untuk mencari ikan di laut.
Setelah mencoba beberapa kali sabu-sabu secara gratis, ketika itu mereka mulai ketagihan. Namun mereka tidak diberikan lagi secara gratis, namun harus membeli sendiri. Maka mereka pun membeli sendiri sabu-sabu ketika akan pergi mencari ikan di laut.
Saat itu mereka membeli sabu 0,5 gram brutto dengan harga Rp200 ribu, lalu ditangkap pihak Kepolisian. Dan ketika ditanyakan untuk apa sabu ini, lalu dijawab untuk dipakai sendiri, karena membuat mereka merasa semakin kuat untuk melaut. Namun oleh penyidik pasal yang dikenakan bukanlah Pasal 127 sesuai UU, tapi pasal yang seharusnya dikenakan untuk bandar, pengedar, kurir yaitu Pasal 111, 112 jo 132.
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Pasal 111, 112 memiliki sanksi penjara yang cukup berat, yaitu minimal 4 tahun, dan maksimal bisa hukuman 20 tahun, bahkan hukuman mati. Hal inilah yang dijadikan materi dalam pembelaan Penulis sebagai penasihat hukum dari dua orang nelayan penyalahguna narkotika tersebut.
Selain merujuk pada Pasal 127 UU ini, Penulis merujuk pula pada Surat Edaran baik di Internal Kepolisian (Kapolri, Kabareskrim), Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung maupun putusan-putusannya mengenai penanganan perkara terhadap penyalahguna atau pecandu narkotika, dengan syarat, kriteria yang cukup jelas juga telah dijadikan dasar dalam pendampingan dan pembelaan.
Namun pihak Kepolisian dan Kejaksaan tetap tidak bergeming menggunakan Pasal 111,112 jo 132 dengan menuntut penjara selama 4 tahun. Bagaimana dapat diterima secara logis penyalahguna atau pecandu narkotika, dengan barang bukti sabu-sabu dengan berat 0,4 gram, diminta, dituntut untuk dipenjara selama 4 tahun. Tuntutan atau permintaan yang menurut terdakwa maupun penasihat hukum jauh dari rasa keadilan.
Kedua orang nelayan ini, pada tingkat Pengadilan Negeri Batam, divonis sama dengan tuntutan dari penuntut umum, yakni 4 tahun penjara. Lalu diajukan upaya banding, dengan menguatkan putusan PN Batam. Lalu diajukan upaya kasasi, dan di sinilah terdapat titik terang terdakwa sebagai pencari keadilan, di mana hakim agung menyatakan para terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, dan divonis 1,6 tahun penjara.
Kedua nelayan ini, bernasib jauh berbeda dengan banyak penyalahguna atau pecandu lainnya, yang dihukum dengan Pasal 111, 112, 113, 114 jo 132, dengan hukuman penjara rata-rata 5 sampai 7 tahun, dengan barang bukti sabu rata-rata 0,1 s/d 1 gram atau ganja beberapa linting saja.
Pasal 127 yang adalah Ius Constitutum (hukum positif), seolah masih menjadi Ius Constituendum (hukum yang dicita-citakan) dalam praktik penerapannya. Pasal 127 ini pula dapat dijadikan ruang “transaksional” pasal dari oknum penegak hukum yang sering dikenakan pada pejabat atau artis, namun jarang tergapai bagi masyarakat kecil, menengah awam hukum yang menjadi korban penyalahguna atau pecandu narkotika.
Tujuan UU
Tujuan dari hukum/UU adalah kepastian, perlindungan dan kemanfaatan. Maka jika menilik dari frasa Pasal 111, 112, 113, 114 yang terdapat frasa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika” sesungguhnya telah terdapat ketidakpastian dalam aturan pasal ini. Sebagaimana Penulis jelaskan dalam materi pleidoi (pembelaan) maupun pertimbangan dari hakim agung dalam putusannya, menyatakan frasa kata “memiliki, menyimpan, menguasai” harus diartikan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dari memiliki, menyimpan, menguasai narkotika tersebut.
Apakah dengan tujuan untuk mengedarkan, menjual atau sebagai perantara/kurir. Maka dapat dikenakan Pasal 111, 112, 113, 114? Karena setiap penyalahguna atau pecandu yang membeli narkotika, pasti terlebih dahulu memiliki, menyimpan, menguasai narkotika tersebut untuk selanjutnya digunakan/dipakainya. Hal inilah yang harus dibedakan dalam pengertian dan penerapan Pasal 127, memiliki narkotika dengan tujuan untuk menggunakan sendiri, dengan pengertian dan penerapan Pasal 111, 112, 113, 114 memiliki narkotika, dengan tujuan untuk mengambil keuntungan.
Dari sisi perlindungan, maka para penyalahguna atau pecandu yang seharusnya dilindungi dengan dibedakan pasal yang dikenakan kepadanya, tapi dalam praktik sering tidak terlindungi, karena dikenakan pasal yang seharusnya untuk bandar, pengedar, atau kurir. Sehingga hak dari para penyalahguna untuk dikenakan/diadili dan dihukum sesuai Pasal 127 dengan hukuman rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun, tidak didapatkan para penyalahguna atau pecandu narkotika tersebut.
Atau masih banyak juga cerita mengenai warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia, dijadikan kurir untuk membawa narkotika dengan jumlah besar dari negeri Jiran tersebut. Para kurir tersebut ada yang mau karena tekanan ekonomi, dan juga intimidasi/ancaman.
Bayaran yang mereka terima pun sangat kecil, namun risiko yang mereka terima besar, dikenakan dengan pasal sebagai seolah-olah bandar besar pemiliki narkotika tersebut. Ancaman penjara yang dikenakan umumnya di atas 10 tahun dan ada yang maksimal hukuman mati. Namun, yang memproduksi atau bandar besar sesungguhnya, belum tersentuh sama sekali.
Dari sisi kemanfaatan, hal ini yang menurut Penulis paling berdampak luas. Pertama, jika kita lihat dari sisi penyalahguna atau pecandu narkotika tersebut, sudah jelas tidak ada manfaatnya sama sekali penyalahguna atau pecandu narkotika dimasukkan dalam penjara dengan waktu yang cukup lama (rata-rata 4-6 tahun).
Bahkan malah lebih banyak ke arah merugikannya, karena banyak anak muda yang terkena narkotika, yang seharusnya dalam masa-masa produktif, dapat direhabilitasi/disembuhkan, dan diarahkan untuk kegiatan yang positif dan produktif. Bahkan ada penyalahguna atau pecandu usai dipenjara malah menjadi pengedar atau bahkan bandar narkotika lantaran di dalam penjara bergaul dengan para bandar.
Kedua, dari sisi negara/pemerintah, sudah jelas pula tidak ada kemanfaatannya. Bahkan timbul permasalahan baru yaitu hampir seluruh Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan yang ada sudah over capacity. Sekitar 60% s/d 70% isinya adalah tahanan/napi narkotika. Anggaran negara pun hingga triliunan digunakan untuk memberi makan tahanan/napi dan untuk membangun Rutan/LP yang baru sehingga bukan kemanfaataan, malah mudarat yang didapat.
Akhirnya Penulis berpendapat, ternyata mengirimkan orang ke penjara bukanlah satu-satunya solusi permasalahan narkotika, khususnya bagi penyalahguna atau pecandu narkotika. Hukumlah seseorang sesuai kesalahannya. Korban penyalahguna atau pecandu narkotika, jika tidak dihukum sesuai dengan pasal yang seharusnya, maka menjadi korban lagi. Korban dari salah jalan, pergaulan, dan korban dari praktik penegakan hukum.
Maka, agar permasalahan narkotika ini tidak berlarut, dan semakin bertambah kompleks, di awal tahun yang baru ini, dengan semangat dan harapan yang baru pula, maka hal yang lalu yang selama ini dilakukan dirasa kurang tepat dan efektif dalam penanganan perkara narkotika, dapat dijadikan koreksi/introspeksi bagi aparat penegak hukum khususnya (polisi, jaksa, hakim) maupun masyarakat secara umum. Agar tujuan dari hukum yaitu kepastian, perlindungan, kemanfaatan dari hukum itu sendiri dapat terpenuhi, sehingga tercapailah proses dan putusan-putusan yang berkeadilan bagi setiap orang.
*)Eric Manurung, S.H. (Advokat)
https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-oleh--eric-manurung/